MENERKA ARUS RADIKALISASI DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA
“Agama yang sebenarnya memiliki misi menciptakan perdamaian, justru terlibat dan dilibatkan dalam konflik” (Halaman 2)
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya mengenai tipologi keislaman yang ada di dalamnya. Terlebih lagi sebagai negara kepulauan (archipelagic state), sering dijumpai umat Islam yang tidak hanya memiliki kesatuan identitas melainkan juga perbedaan dan keragaman adat serta budaya.
Pembahasan mengenai keberagaman juga tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam dan berujung pada aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia. Kelompok ini dapat digolongkan sebagai golongan ekstrim yang menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan Negara. Kerugian tersebut berupa jatuhnya korban tak bersalah melalui aksi pengeboman yang dianggap mereka sebagai bentuk jihad, serta rusaknya berbagai fasilitas publik. Peristiwa bom Bali I (Oktober 2001) dan bom Bali II (Oktober 2005) membuktikan hal tersebut.
Arus radikalisme hingga hari ini menjadi suatu hal yang terus menerus dikupas guna mencari solusi yang terbaik. Berbicara mengenai radikalisme adalah berbicara mengenai proses deradikalisasi. Sebenarnya sudah sejak lama deradikalisasi diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selaku ormas Islam terbesar di negeri ini. Tentunya dengan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang satu yakni Indonesia sebagai negara majemuk yang hidup dengan perbedaan secara damai.
Akan tetapi faktanya, kekerasan yang terjadi mengatasnamakan agama seolah abadi dan terus bermunculan tiada henti. Oleh karenanya diperlukan adanya sebuah pemahaman makna baru yang lebih luas mengenai deradikalisasi itu sendiri.
Pembaharuan perspektif mengenai deradikalisasi tidak lagi harus dimaknai sebatas pemutusan terhadap keterlibatan ideologi dan praktik kekerasan saja. Indonesia membutuhkan pemahaman yang lebih luas lebih daripada itu. Deradikalisasi haruslah bermakna sebagai usaha untuk membangun kualitas peradaban manusia di bidang sosial dan ekonomi seluruh individu, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta usaha mewujudkan keadilan sosial.
Arus radikalisme yang dimulai pasca jatuhnya rezim orde baru pada 1998 hingga pasca reformasi, rupanya memberikan ruang yang luas bagi bermacam-macam kelompok atau organisasi islam untuk mulai mendapatkan panggung untuk menyuarakan kebebasan yang telah dijamin undang-undang. Tak terkecuali bagi golongan islam garis keras (Hardliners) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, HTI juga bisa digolongkan sebagai gerakan Islam transnasional (GIT) karena memiliki jejaring yang melewati lintas batas negara. Selain HTI, terdapat juga organisasi Islam lokal yang cukup memiliki daya tarik sangat kuat saat ini seperti Front Pembela Islam (FPI).
Menurut HTI, perubahan haruslah dimulai dengan mengganti keseluruhan sistem yang ada. Tidak cukup perubahan dilakukan secara gradual ataupun parsial dengan hanya mengganti seorang pemimpin. HTI meyakini bahwa sistem demokrasi, kapitalisme maupun seluruh ideologi produk barat menyebabkan rakyat semakin sengsara. Sasaran penyebaran ideologi HTI dilakukan melalui pendidikan yang mengedepankan syariat Islam.
Berbeda dengan HTI melalui konstruksi pendidikan yang dimiliki, berbeda pula dengan konstruksi pendidikan oleh Syiah yang juga dipaparkan oleh buku ini. Konstruksi pendidikan Syiah jauh lebih kritis dibandingkan dengan HTI yang cenderung dogmatis. Syiah melalui pesantren YAPI yang terletak di Bangil – Jawa Timur lebih mengafirmasi mengenai kebebasan berfikir santrinya sehingga para santri yang menganut paham sunni mendapatkan kebebasan tanpa berhadapan sama sekali dengan ideologisasi atau indoktrinasi yang cenderung dogmatis. Melalui buku ini, penulis memberikan gambaran perbedaan diantara keduanya dengan sangat moderat.
Menanggapi berbagai fenomena tersebut, buku ini hadir melalui konsep multikulturalisme. Syamsul Arifin sebagai penulis buku ini menawarkan konsep multikulturalisme sebagai daya pemersatu bangsa. Sedikit mengenai penulis, Syamsul Arifin adalah Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kelahiran Sampang, Madura, 22 Desember 1967. Penulis adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus dengan disertasi yang membahas tentang Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia.
Melalui konsep multikulturalisme ini, hal pertamayang harus dilakukan adalah memahami bahwa manusia tidaklah hidup di ruang yang hampa dan akan selalu menemui perbedaan dalam cara pandang terhadap dunia di antara tiap-tiap individu. Kompleksitas perbedaan inilah yang menuntut sebuah pendidikan multikulturlisme agar dapat menjadi kendaraan dalam menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Multikulturalisme merupakan ruang untuk manusia berbagi di tengah-tengah perbedaan yang ada. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa adanya kearifan dan keinginan batin untuk saling berbagi dan toleran atas perbedaan. Oleh karenanya, manusia yang arif hendaknya mendamaikan batinnya terlebih dahulu sebelum menebarkan pesan-pesan perdamaian. Sehingga yang menjadi tantangan hari ini ialah bagaimana institusi pendidikan, terutama yang dimiliki umat Islam untuk juga bekerja dengan institusi lainnya guna menampilkan wajah Islam yang lebih harmonis dan toleran.
Buku ini berusaha mengupas mengenai bagaimana pendidikan multikulturalisme diterapkan serta perjalanan panjang dalam menerapkan deradikalisasi melalui berbagai konsep para ahli yang berkaitan sebagaimana dikutip oleh penulis. Buku ini mampu memberikan berbagai khazanah pengetahuan terkini mengenai konsep-konsep yang sangat menarik dan relevan sesuai dengan pembahasan yang ada. Selain itu, buku ini digarap dengan penelitian langsung ke lapangan sehingga memberikan data yang cukup akurat dan faktual.
Berbeda dengan buku karya Saefuddin Zuhri yang berjudul “Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama” yang membahas mengenai proses deradikalisasi melalui konsep Civil Society dengan representasi NU, Muhammadiyah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sementara buku ini, lebih menekankan pada konsep dan implementasi multikulturalisme secara umum. Permasalahan mengenai kekerasan sebagai dampak dari berbedanya pandangan dunia yang dimiliki oleh masing-masing individu maupun kelompok juga tidak bisa dilepaskan dari perbedaan interpretasi yang dimiliki oleh masing-masing (individu dan kelompok) tersebut. Berbeda pula dengan buku karya Mun’im Sirry yang berjudul, “Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama” yang membahas mengenai perbedaan mendasar mengenai perbedaan interpretasi tersebut melalui kajiannya terhadap al-Quran dan hadist yang kemudian memiliki pengaruh tersendiri terhadap arti toleransi dan multikulturalisme.
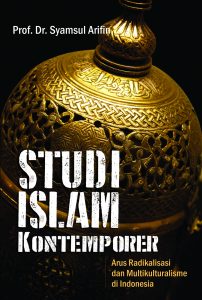 Judul : Studi Islam Kontemporer : Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia
Judul : Studi Islam Kontemporer : Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia
Penulis : Prof. Dr. Syamsul Arifin
Penerbit : Intrans Publishing
Tahun Terbit : 2015
Tebal : xxx + 304 Halaman
Resentor : Muhammad Alaydrus


